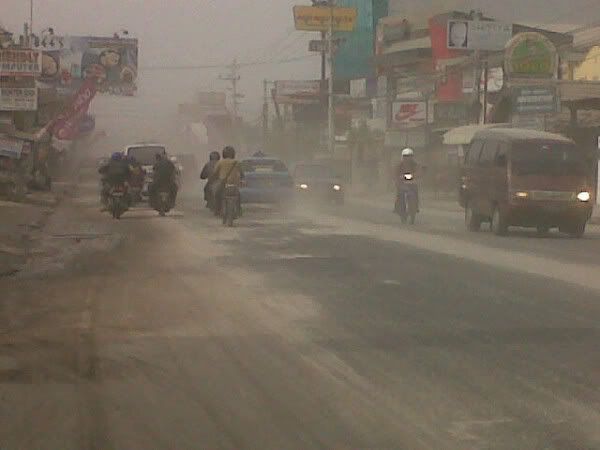Hai semua! Buat kalian yang suka sama kajian Tionghoa di Indonesia, monggo dicicipi tulisan saya yang beberapa waktu lalu dimasukin di sebuah jurnal mahasiswa, #Keren ya? Pemulung punya komputer dan bisa nulis sejarah! Abisnya jadi pemulung gaptek dan kere ga asik, di kecengin terus sama temen-temen sesama pemulung, hehe.
Jadi-jadi. . . tulisan ini mungkin anggap aja sebagai persembahan buat kalian dan terutama mas Dwicipta yang menyempatkan diri menemui saya yang masih kroco, #maklum, mas-mas satu ini sudah berkaliber nasional, cerpennya aja dapat anugerah dari koran Kempes #eh KOMPAS, hahaha, jadi sekali lagi terimakasih buat diskusinya yang selalu asyik, entah dia sekarang dimana, semoga secepat e rabi, biar ga munyeng aja keliling-keliling Jawa. hahaha, cekidot!
Pengantar
Setelah Jepang bertekuk lutut kepada sekutu yang menjadi pemenang pada laga
Perang Dunia II. Indonesia sebagai
bangsa yang terjajah mulai bangkit untuk menjalani babak baru menjadi sebuah
entitas politik yang berdaulat dan berusaha sejajar dengan negara-negara
manapun di dunia. Tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak awal revolusi
nasional bangsa Indonesia yang ditandai dengan dicetuskannya Proklamasi
Kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta. (Kahin, 1990: 11) Bertolak dari proklamasi
kemerdekaan tersebut, di berbagai daerah hampir bersamaan muncul
gerakan-gerakan pendaulatan dimana targetnya tak lebih dari sisa-sisa pendukung
tatanan kolonial Belanda dan pendudukan Jepang yang tercipta belakangan (Cribb,
1990: 7). Aksi “pembersihan” secara sepihak yang terjadi di daerah tidak hanya
menyapu kalangan atas saja –dimana sebelumnya raja-raja tradisional, para
bangsawan kecil dan kelompok birokrat memiliki pengaruh di masa-masa sebelum
kemerdekaan–, tetapi juga menimpa kalangan bawah, terutama orang-orang Indo dan
Tionghoa. Tindakan tersebut dapat terjadi karena respon dari masyarakat
bumiputra yang menganggap orang Tionghoa memiliki “hubungan” dengan Belanda –meskipun
di Medan gerakan protes untuk meminta perlindungan kepada sekutu baru muncul
setelah aksi kekerasan terjadi. Di Surabaya sendiri perlawanan terhadap
pandangan buruk tersebut ditunjukkan oleh komunitas Tionghoa di kota itu dengan
turut aktif dalam perjuangan melawan Belanda. Akan tetapi kekerasan tetap merupakan
fenomena tersendiri pada masa-masa awal revolusi Indonesia.
Tibanya
sekutu guna mengambil alih kekuasaan Jepang di Indonesia ternyata menimbulkan
tantangan-tantangan serius yang pertama terhadap revolusi. Inggris yang menjadi
penanggung jawab pendaratan sekutu di wilayah Asia Tenggara ternyata tidak
sendiri, mereka diboncengi oleh NICA (Netherlands
Indies Civil Administration). Diawali dari pendaratan pertama di bulan
September 1945, pasukan sekutu (Inggris dan NICA) berhasil masuk ke Jakarta
untuk melepaskan kaum internir-an Jepang. Keadaan ini seringkali memicu bentrokan
senjata dengan badan perjuangan setempat. Revolusi Nasional yang dimulai dari Jakarta
rupanya merembet hingga ke kota-kota besar lainnya di Jawa dan Sumatra,
kembalinya penguasa lama menjadi ancaman laten terhadap kemajuan-kemajuan yang
telah dicapai oleh pihak Republik.
Masa
Bersiap, begitulah pemuda-pemuda revolusioner menyebutnya sangat terasa pengaruhnya
di Surabaya. Pada akhir Oktober 1945, sekitar enam ribu prajurit sekutu yang
terdiri dari serdadu Inggris, Gurkha, dan anggota NICA mendarat di kota ini.
Kehadiran mereka membuat keadaan semakin tegang dan tak menentu. Seperti di
Jakarta, alih-alih membebaskan tawanan perang, pihak Belanda rupanya juga
mempersenjatai para tawanan dan mempengaruhi etnis Tionghoa di kota ini untuk
memihak mereka guna membangun kembali kekuasaannya (Roeslan Abdulgani, 1973:
23). Strategi ini rupanya berhasil, dimana beberapa penduduk Tionghoa Surabaya berdinas
dalam pasukan atau menjadi mata-mata Belanda. Keberpihakan ini nyatanya tidak
hanya dilakukan etnis Tionghoa saja, banyak juga diantaranya orang-orang
bumiputra (K’tut Tantri, 2006: 215-216). Menggadaikan kesetiaan bukanlah jalan
yang patut ditempuh, akan tetapi kemiskinan yang membelit akibat kekacauan dari
negara yang “mungkin” tidak terselamatkan menjadi satu-satunya pilihan rasional.
Hal ini tentu saja menuai reaksi bagi penduduk Tionghoa yang pro-Republik,
hingga berujung bentrokan yang menewaskan seorang Tionghoa yang mendukung
kemerdekaan. Arek-arek Surabaya yang
tergabung dalam BKR (Badan Keamanan Rakyat) dan Barisan Pemuda Tionghoa segera
mengambil sikap. Mereka bersama-sama menyusun daftar hitam orang-orang Tionghoa
yang bekerja sebagai mata-mata musuh (Andjarwati Noordjanah, 2010: 111). Aksi pembersihan
yang dilakukan menimbulkan ketakutan bagi penduduk Tionghoa yang tinggal di
kota.
Keresahan
mulai memuncak ketika Surabaya diguncang pertempuran hebat pada tanggal 10
November 1945. Sebagian besar penduduk kota baik penduduk lokal maupun Tionghoa
mengungsi ke wilayah selatan. Sedangkan mereka yang lebih memilih untuk tetap
tinggal berada di dalam lindungan Panitia Keamanan Rakyat (PKR). Penggerak
lembaga multietnis ini dipimpin oleh seorang pribumi walau kekuatan penggerak
sebenarnya dalam organisasi ini adalah Tionghoa yang bernama Oei Chiao Liong.
PKR merupakan suatu bentuk kerjasama antara penduduk Tionghoa dan penduduk
bumiputra non politik yang berusaha menjaga keamanan dan mengurus kepentingan
warga Tionghoa dan Indonesia yang tidak ikut mengungsi. Selain itu terdapat
lembaga sosial non politik lain seperti Palang Merah Tionghoa yang bertugas
memberikan pelayanan kesehatan kepada warga Surabaya dari berbagai etnis
(Somers Heidhues, 1991: 167).
Untuk
mengantisipasi bocornya informasi ke pihak musuh, para pemuda kembali melakukan
pembersihan terhadap mata-mata Belanda. Dalam sebuah penggalan cerita pendek
yang ditulis Idrus dengan judul Surabaya,
perasaan takut tergambar jelas di benak rakyat Surabaya terhadap para
pengkhianat Republik:
"Rakyat cukup berani
menghadapi meriam-meriam musuh…. namun betapa takut mereka terhadap mata-mata
musuh. Pemandangan yang mengerikan itu menghembus bagaikan badai di atas
kota-kota dan di dalam hati kaum lelaki, meratakan segala sesuatu di jalannya –
baik keberanian maupun kerasionalan. Setiap orang curiga terhadap semua orang
lainnya, dan untuk membebaskan diri dari siksaan pemandangan ini mereka saling
membunuh" (Reid, 1996: 89).
Ketakutan
berujung pada kecurigaan tersebut terbukti nyata. Seorang Tionghoa menjadi korban
ketika operasi pembersihan dilakukan, dirinya dianggap sebagai mata-mata Belanda.
Barang-barangnya disita kemudian orangnya dibakar hidup-hidup di Alun-alun
Sidoarjo. Dugaan bahwa NICA menandai mata-matanya dengan tanda khusus, berkembang
menjadi sesuatu yang tidak dapat dinalar, dimana banyak orang dibunuh hanya
karena kebetulan pakaiannya mempunyai unsur-unsur warna bendera Belanda. Adakalanya
isu-isu negatif maupun teror yang terjadi sengaja ditiupkan oleh pihak Belanda
untuk memperkeruh keadaan. Taktik itu memang dilakukan agar sistem segregasi
dan kebencian antar ras tetap tertanam diantara kemajemukan masyarakat
Indonesia (Pramoedya Ananta Toer, 1998: 165). Terbunuhnya pengungsi yang
dicurigai mata-mata Belanda membawa akibat yang buruk terhadap nama baik
pemerintah dan pejuang Indonesia di Surabaya. Pihak BPRI (Barisan Pemberontak
Republik Indonesia) sendiri segera mengambil tindakan dengan mengumumkan bahwa
serangan terhadap warga asing tidak dibenarkan dan harus dihentikan.
(Andjarwati Noordjanah, 2010: 131).
Ketika
tersiarnya berita tentang proklamasi, banyak rakyat Indonesia yang tinggal di
luar Jawa tidak mempercayainya. Di Sumatera Utara, faktor hubungan sosial
multi-etnis dan suasana ketidakharmonisan yang terbentuk pada masa-masa
sebelumnya, membuat informasi kemerdekaan menjadi simpang siur. Hanya dalam
beberapa minggu, isu tersebut berkembang menjadi suatu kecurigaan antar lapisan
sosial dan konflik yang bersifat vertikal dan horizontal (Reid, 1996: 111). Sikap
berbeda ditunjukkan oleh penduduk Tionghoa Medan, dimana kemerdekaan tidak
mendapat tanggapan serius dari dalam komunitas ini. Mereka lebih memilih diam
dan menunggu hingga semuanya menjadi jelas. Pedagang-pedagang Tionghoa yang
memiliki kios di pasar maupun di Pecinan memilih tutup sebagai langkah
antisipasi dari tindak kriminal.
Kebenaran
tentang kemerdekaan Indonesia mulai menguat ketika Mr. Teuku Mohammad Hasan tiba
di Medan dengan membawa “oleh-oleh” dari Jakarta. Ia tidak gegabah, dialog dengan
Shu Sangi Kai yang dipimpin Dr. T.
Mansjoer hal pertama yang harus dilakukan, mengingat masih kuatnya otoritas
yang dimiliki keenam kesultanan di Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara
tersebut menyampaikan pesan untuk secepatnya menyampaikan kabar kemerdekaan
untuk rakyat Medan dan segera membentuk pemerintahan daerah, akan tetapi dialog
tersebut tidak menemukan titik temu. Hal ini terjadi karena pada dasarnya
mayoritas bangsawan Melayu menginginkan kembalinya pemerintahan Belanda di
wilayah ini. T.M. Hasan mulai mendapatkan angin segar ketika dukungan penuh datang
dari BKPI (Barisan Kebaktian Pemuda Indonesia) dan organ-organ perjuangan
lainnya (Nasrul Hamdani, 2013: 145-146).
Pada
tanggal 6 Oktober ketakutan akan semakin meruncingnya sentimen antar lapisan
sosial menjadi nyata. Pada saat penobatan Sultan Otteman menjadi Sultan Deli yang
baru, di depan istana berkibar bendera Merah-Putih-Biru disamping bendera
Kesultanan Deli. Sore harinya aksi tandingan dilakukan oleh pemuda dengan
mengibarkan bendera Merah-Putih, dimana pembacaan kembali teks proklamasi
dilakukan oleh T.M. Hasan –Gubernur Sumatera Utara yang ditunjuk oleh pemerintah
pusat (Reid, 1987: 271). Pasukan Belanda dan Sekutu sebenarnya telah bercokol
di Sumatera Utara sejak bulan Oktober 1945, tapi mereka tidak dapat berbuat banyak
karena kekurangan personil. Sekarang tampak jelas siapa yang menjadi Republiken dan siapa yang memihak Belanda.
Keadaan semakin memanas pada saat pihak NC (National Control) yang dipimpin
Xarim M.S. mulai menghembuskan “momentum” bagi sebuah pertukaran rezim dan
perimbangan kekuasaan. Agitasi inilah yang kemudian menyulut semangat rakyat hingga
menjadi sebuah revolusi sosial di Medan.
Pada
masa-masa awal dimulainya revolusi sosial, penduduk Tionghoa banyak mengalami
gangguan dengan alasan politik maupun ekonomi. Kelompok-kelompok ini secara
teratur merampoki toko-toko dan gudang-gudang milik Tionghoa sekaligus menyita
barang-barang yang menurut kabar sengaja ditimbun (van Langenberg, 1990: 139).
Perampokan yang berkedok “perjuangan” tersebut membuat Tjamboek Berdoeri (Kwee Thiam Tjing) angkat bicara. Lewat
tulisannya ia menuturkan bahwa:
“Djamino
dan Djoliteng gespuis (bajingan),
marika itoe di zaman revolutie mendjadi pemboenoeh, toekang perkosa, toekang
bakar roemah pendoedoek jang tida berdosa, toekang sembeleh korban-korbannja
jang majit-majitnja kamoedian ditoewangin benzene boeat dibakar!....., Jang
golongan Djamino dan Djoliteng dari bangsa apa djoega seringkali bikin moemet (pusing) kepala dari
pemimpin-pemimpinnja, ini bisa dimengerti” (Tjamboek Berdoeri, 2004: 292-293).
Demonstrasi Orang Tionghoa di Medan
(www.budayationghoa.net)
Terbatasnya
peran negara dalam mengontrol barisan-barisan ini disebabkan posisi Republik saat
itu sedang kacau sehingga koordinasi antara pusat dan daerah tidak berlangsung
semestinya. Sedangkan pemerintah daerah tidak memiliki otoritas yang kuat atas
kegiatan-kegiatan yang dilakukan kelompok-kelompok pejuang. Pada intinya gangguan
atas etnis Tionghoa di Medan merupakan kelanjutan dari aksi “pembersihan” atas
golongan aristokrat yang ambruk dihempas kemarahan massa. Meski tidak ada
alasan yang tepat untuk memusuhi Tionghoa, akan tetapi perbedaan identitas,
orientasi dan yang paling mendasar adalah kuatnya peran mereka di bidang
ekonomi, maka jadilah mereka sebagai musuh bersama (Nasrul Hamdani, 2013: 160).
Lahirnya
Pao An Tui: Berawal dari Suatu
Kepedulian
Aksi
penjarahan yang terjadi seiring meningkatnya konflik antara Indonesia-Belanda
ternyata terus berlangsung dan merembet ke arah pembantaian (Ricklefs, 2008:
459-464). Di beberapa wilayah, peristiwa yang menimpa warga Tionghoa menjadi
pemandangan sehari-hari meskipun beberapa dari mereka mendukung kemerdekaan
Republik Indonesia. Pihak Republik berusaha mencari pembenaran terhadap apa
yang terjadi. Menurut mereka, tindakan tersebut terjadi karena keterlibatan
beberapa orang Tionghoa yang berdinas dalam pemerintahan Belanda. Untuk
mencegah tindak kekerasan terulang kembali, pihak Republik meminta Belanda
untuk berhenti menyerang dan mempergunakan orang Tionghoa untuk tujuan mereka,
akan tetapi protes ini tidak digubris.
Situasi
bertambah parah ketika Belanda melakukan “aksi polisional”-nya yang pertama,
untuk menghambat gerak maju Belanda pihak Republik melaksanakan strategi bumi
hangus. Ini dimaksudkan agar aset-aset yang ditinggalkan pejuang dan rakyat
tidak dimanfaatkan oleh personil Belanda. Tak pelak, orang Tionghoa-lah yang
paling dirugikan dalam strategi ini sebab tempat-tempat yang menjadi target
pembumihangusan sebagian besar milik mereka. Melihat situasi yang kacau
disertai aksi-aksi kekerasan, hal tersebut rupanya mengundang perhatian
pemerintah Cina untuk mencarikan solusi atas apa yang terjadi. Konsul Jenderal
Tiongkok Tsiang Chia-tung mengeluarkan intruksi:
Kepada
orang-orang Tionghoa yang berdiam di daerah Republik agar mereka menolak
apabila dipindahkan keluar batas kota dan apabila menghadapi bahaya, mereka harus
berkumpul bersama di bangunan sekolah atau perkumpulan dan mengibarkan bendera
Tiongkok bersama bendera palang merah (Benny G. Setiono, 2008: 629).
Sebagai jawaban atas seruan
tersebut unit-unit sukarela segera dibentuk di distrik-distrik Tionghoa di berbagai
kota besar, akan tetapi usaha ini tidak banyak membawa hasil.
Akibat
terjadinya kekacauan yang telah menimbulkan banyak penderitaan kepada etnis
Tionghoa sebagai ekses aksi militer Belanda, timbul pemikiran sejumlah tokoh
peranakan Tionghoa di Jakarta untuk mencari jalan agar kejadian serupa tidak
terulang kembali. Perkumpulan Chung Hua
Tsung Hui (CHTH) Jakarta memiliki inisiatif untuk
mengadakan konferensi yang terdiri dari perwakilan-perwakilan CHTH seluruh
Indonesia. Konferensi Tionghoa ini rencananya akan
diadakan di Gedung Sing Ming Hui Jakarta
selama tiga hari, mulai dari tanggal 24-26 Agustus 1947. Setelah melalui
persidangan yang panjang akhirnya tercetuslah beberapa keputusan:
1.
Pembentukan Pao An Tui (Badan Pelindung Keamanan Tionghoa)
2.
Mendirikan suatu badan penyiaran resmi
3.
Menyebarluaskan hasil keputusan ke dalam dan
luar negeri
4.
Koordinasi untuk menolong korban-korban yang
akan dibentuk di setiap daerah (Sulardi, 1994: 62-63).
Tanggal 29 Agustus 1947
merupakan hari dimana Pao An Tui disahkan
berdasarkan keputusan rapat perwakilan Tionghoa Indonesia yang tergabung ke
dalam Chung Hua Tsung Hui Lien Ho Pan She
Tsu (Badan Koordinasi CHTH Indonesia) –salah satu anggotanya ialah Kwee Kek
Beng--, dan Jakarta dipilih
sebagai kantor komite pusat. Keberadaan Pao
An Tui –setelahnya akan digunakan kata PAT– tergantung pada berlakunya masa
darurat perang yang berarti sewaktu-waktu organisasi ini dapat dibubarkan.
Beberapa
hari sebelumnya Konsul Jenderal Tiongkok, Tsiang Chia Tung lewat siaran radio Batavia
memberitahukan bahwa orang-orang Tionghoa yang berada di wilayah pendudukan
Belanda diberi kebebasan untuk mendirikan badan keamanan sendiri. Srdangkan penduduk
Tionghoa yang tinggal di dalam wilayah republik jika dirasa perlu diperbolehkan
membentuk badan keamanan serupa. Himbauan tersebut ditolak mentah-mentah oleh
pemerintah RI karena mereka yakin keselamatan etnis Tionghoa di wilayahnya
terjamin dan tidak ada yang mendapat perlakuan istimewa (A.H. Nasution, 1977:
35). Selain itu masyarakat Tionghoa yang ada di daerah republik juga menyadari
jika mereka membentuk badan keamanan sendiri, maka posisi mereka sangat tidak
diuntungkan karena dapat menimbulkan salah paham dengan pihak pejuang.
Kemunculan
PAT pada masa revolusi merupakan sesuatu yang istimewa dimana organisasi ini
mendapat izin dari Belanda, seperti tertuang pada Keputusan Peraturan Penguasa Militer No. 516 yang ditandatangani
oleh Jenderal S.H. Spoor. Ini berarti orang Tionghoa diberi keleluasaan dan di-“anak
emas”-kan karena sebagian besar dari mereka mendukung dan terlibat dalam
kebijakan yang diterapkan Belanda. Hal ini sebuah kewajaran mengingat pada masa
ini Belanda lebih berfokus pada pemulihan keamanan dan perekonomian Indonesia
yang telah lama terkoyak akibat perang. Organisasi kepolisian Tionghoa ini mendapat
tugas dan wewenang untuk melindungi jiwa dan harta milik orang Tionghoa, mereka
akan ikut campur dalam tugas militer apabila dibutuhkan, dan keanggotaannya terbatas
pada orang Tionghoa saja, dan kadang-kadang mempunyai anggota orang Indonesia
(Somers Heidhues, 1991: 172). Lewat tugas dan wewenang yang diperoleh
organisasi ini terlihat jelas bahwa sejak awal Pemerintah Militer Belanda ikut
campur tangan. Selain melihat seberapa besar dukungan dan afiliasi komunitas
Tionghoa terhadap Belanda, secara tidak langsung tugas mereka lebih diringankan
karena keselamatan hidup orang Tionghoa beserta aset-asetnya sudah terwakilkan
lewat PAT. Selain itu, lembaga ini juga dapat dijadikan pasukan cadangan jika sewaktu-waktu
dibutuhkan.
Dari
Kontroversi Menjadi Aksi
Setelah
disahkan oleh komite, dengan cepat PAT bermunculan di daerah-daerah kekuasaan
Belanda yang menjadi pusat konsentrasi komunitas Tionghoa. Kemunculan
organisasi semi militer ini lebih banyak terdapat di Jawa dan Sumatera saja, meliputi
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur untuk Pulau Jawa, sedangkan di Sumatera
mereka terdapat di daerah Sumatera Timur dan Sumatera Barat (Sulardi, 1994:
66-67). Jakarta dipilih menjadi kantor pusat PAT dari seluruh Indonesia, karena
disini merupakan pusat pemerintahan sekaligus menjadi pusat kegiatan utama yang
mengurusi segala bentuk administrasi lembaga ini.
Surabaya
dalam beberapa hal menjadi kota yang “berbeda” pada masa awal kemerdekaan. Sejak
semula penduduk Tionghoa ini terpecah ke dalam dua arus yang berbeda.
Orang-orang seperti Tjoa Sik Len, Siauw Giok Tjan dan Tan Po Goan lebih memilih
untuk condong ke Republik, sedangkan yang lain menjadi pro-Belanda. Setelah
proklamasi, peran nyata diberikan oleh mereka-mereka yang pro-Republik dengan
cara membantu segenap tenaga perjuangan pemuda Surabaya. Akan tetapi disaat
kacau tersebut, seringkali orang Tionghoa mendapat perlakuan diskriminasi dan
kekerasan dalam banyak hal. Perlahan namun pasti, orang-orang Tionghoa yang
pro-kemerdekaan mulai kehilangan pengaruhnya di kota besar itu, sedangkan etnis
Tionghoa yang dekat dengan Belanda mulai bangkit seiring dilaksanakannya Agresi
Militer Belanda pertama.
Setelah
kembali dari rapat umum CHTH seluruh Indonesia. Dua kubu yang saling berbeda pandangan
ini melakukan rapat internal. Mayoritas organisasi komunitas Tionghoa Surabaya
mendapatkan suara bulat terhadap orang-orang pro-Republik. Atas desakan AM
(Abdi Masyarakat) mereka melakukan pemboikotan atas pembentukan Pao An Tui (Andjarwati Noordjanah, 2010:
113). Seruan penolakan juga muncul dari Tjamboek
Berdoeri (Kwee Thiam Tjing) terhadap ide bangsanya sendiri, yang secara
getir menyatakan bahwa:
“Sebagimana
pembatja tahoe, Pao An Tui dilahirken
di atas toempoekan poeing dan majit-majit sebagi soembangan decoratie dari
fihaknya pendoedoek Tionghoa boat bikin lengkep Djamino dan Djoliteng
Indonesier poenja pertoendjoekan lelakoen di panggoeng doenia”
.
dan pandangannya tentang rencana
pembentukan PAT Malang:
“Di
Malang sendiri, niatan diriken Pao An Tui
mendjadi serabi tida, koetjoer poen boekan. Satoe hal jang biasa bagi siapa
jang kenal Malang poenja pendodoek Tionghoa” (Tjamboek Berdoeri, 2004: 300).
Sebuah
organisasi PAT segera dibentuk di Surabaya pada akhir 1947. Perekrutan yang
dilakukan diambil dari pemuda-pemuda Tionghoa yang berusia 18-25 tahun.
Masuknya mereka menjadi anggota dikarenakan faktor yang beragam, ada yang
mendaftar karena sakit hati dan ingin balas dendam karena sebelumnya keluarga
mereka menjadi korban. Ada pula yang hanya ingin mengejar prestise atau sekedar
mencari nafkah. Tugas utama mereka adalah menjaga pusat-pusat ekonomi,
melindungi tempat tinggal dan tempat pengungsian orang-orang Tionghoa dari
serangan “ekstrimis” Indonesia (Tjamboek Berdoeri, 2004: 299-300), juga
mengadakan patroli kota dan mengamankan daerah-daerah perbatasan.
Sebagai
organisasi paramiliter, ketika bertugas tentunya mereka menggunakan seragam
warna abu-abu layaknya tentara dan memiliki simbol khusus bergambar
pedang/golok yang bersilang di bagian tengah dengan rantai yang melingkar di
sepanjang garis luar dan tulisan PAT dalam huruf Tiongkok dan Latin. Badge ini biasa digunakan di lengan
sebelah kiri. Sekilas seragam yang mereka gunakan mirip seragam KNIL, yang
membedakan hanya lencananya (Sulardi, 1994: 85). Akan tetapi oleh orang luar
terlihat bahwa PAT merupakan bagian dari personil Belanda. Selama bertugas
hanya sebagian kecil dari mereka yang membawa pistol sisanya hanya membawa
pemukul. Pemerintah militer Belanda tidak mengizinkan hal itu karena mereka
takut jika PAT diberi persenjataan lengkap ada kemungkinan mereka akan membelot
dan memihak pejuang Indonesia. Pada awalnya organisasi semi militer ini hanya
mendapatkan tugas sepele, namun tidak jarang mereka mendapat tugas layaknya
anggota militer sesungguhnya. Di medan pertempuran, pasukan ini jelas-jelas
berada di pihak Belanda sehingga tak jarang mereka terlibat dalam bentrokan
langsung melawan gerilyawan-gerilyawan Indonesia.

Anggota Pao An Tui Perempuan
(www.budayationghoa.net)
Diawali
dari serangan-serangan terhadap komunitas Tionghoa di Medan yang intensitasnya
terus meningkat. Akumulasi kekerasan yang terjadi tersebut tak dapat terbendung
lagi hingga menimbulkan demonstrasi masyarakat Tionghoa Medan pada akhir tahun
1947. Sebelum demonstrasi terjadi mereka bahkan telah mengirimkan surat kepada
pemerintah Belanda yang pada intinya meminta perlindungan dari kekejaman
gerombolan laskar dan mendesak untuk membentuk badan kepolisian Tionghoa
seperti di Jawa (Nasrul Hamdani, 2013: 162-166). Hal ini tentu saja medapatkan
respon buruk dari pemerintah lokal Medan dimana Gubernur Sumatera Utara merasa
dilecehkan karena orang Tionghoa terlalu membesar-besarkan apa yang terjadi dan
menginginkan sesuatu yang berlebihan. Permintaan akan dibentuknya badan
perlindungan khusus bagi orang Tionghoa sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya
pihak Inggris dan Republik di Medan sudah terlebih dahulu merestui terbentuknya
polisi keamanan Tionghoa yang biasa disebut CSC (Chinese Security Corps) pada tahun 1946. Secara struktur maupun
tugas CSC tidak jauh berbeda dengan PAT bentukan Belanda, sehingga bukanlah
suatu halangan ketika CHTH merekrut kembali anggota tersebut ke dalam PAT
karena dalam waktu singkat jumlah personil dalam badan tersebut mencapai 800
hingga 1000 orang (van Langenberg, 1990: 140). Fakta menarik diungkapkan oleh
Mary F. Somers Heidhues bahwa anggota Medan:
“Disinyalir
sebagai pasukan nasionalis Tiongkok yang tertangkap semasa perang Tiongkok-Jepang
dan oleh Jepang dibuang ke Sumatera. Setelah dibebaskan sekutu, sebagian
bergabung dengan PAT. Ini menjadi bukti bahwa hubungan pro-Kuomintang sangat
kuat pada satuan keamanan Medan” (Somers Heidhues, 1991: 173).
Tugas
PAT (Chineze Veiligheidcorpsen)
sebenarnya jelas bahwa mereka harus melakukan patroli dan penjagaan di pecinan,
pasar, sekolah hingga tempat pengungsian orang-orang Tionghoa sampai keadaan
normal. Ketika mereka di tempat pengungsian penduduk Tionghoa di perbatasan
garis demarkasi inilah mereka kerapkali bentrok dengan pasukan Republik yang
secara kebetulan juga menjadi area pengamanan para pejuang (Benny G. Setiono,
2008: 547). Tempat-tempat keramaian menjadi obyek vital yang perlu dijaga ketat
untuk mengantisipasi penyusup Republik. Taktik perang kota yang berfokus pada
penggeledahan rumah-rumah juga melibatkan PAT dalam aksinya. Tidak hanya rumah
pribumi, terkadang rumah orang Tionghoa juga menjadi target sweeping untuk memastikan tidak adanya
penyusup Republik. Perilaku mereka pun tidak berbeda dengan gerombolan
bersenjata yang mengaku Republiken.
Setiap aksinya badan semi-militer ini tak jarang melakukan tindakan kasar
seperti mengambil barang penduduk (Nasrul Hamdani, 2013: 172).
Sesekali
PAT kelihatan bertindak sebagai “polisi pribadi” dimana “menahan” kepala SBP
Cina atas desakan Wakil Konsul Cina karena dituduh membiarkan penempelan sebuah
surat kabar dinding yang menyerang Chiang Kai-shek. Untuk melaksanakan tugas tersebut,
kesatuan paramiliter ini diberi perlengkapan tempur yang bisa dibilang lebih
lengkap dibanding PAT di Jawa. Selain senjata sisa dari Inggris mereka
diperkuat oleh senjata laras panjang, pistol revolver, artileri ringan hingga
jip patrol. Akhirnya timbul pertanyaan apakah PAT benar-benar melindungi semua
orang Tionghoa ataukah hanya pengusaha kaya yang tentunya merupakan penyumbang
utamanya selama organisasi itu dibiayai dengan dana masyarakat. seperti
dikemukakan diatas, ada petunjuk bahwa satuan ini hanya untuk melindungi
properti terutama sekali pabrik, kilang, gudang dan perkebunan dari sabotase
atau serangan pembumihangusan.
Masyarakat
Memilih Bersikap
Keberadaan
PAT pada awalnya disegani dan popular di kalangan Tionghoa. Lewat PAT-lah
orang-orang Tionghoa tidak lagi merasa terancam akan tindak kejahatan karena
ada saudara sebangsa yang dapat melindungi kehidupan mereka. Setiap orang akan
berjejal-jejalan di pinggir jalan untuk melihat parade dan tak segan memberikan
semangat bagi para “pahlawan” mereka. Semangat yang diberikan tidak hanya
berupa dukungan moril namun juga dalam bentuk pemberian dana. Akan tetapi
kepopuleran PAT semakin lama semakin meredup karena beberapa faktor. Besarnya
biaya yang ditanggung setiap kepala rumah tangga Tionghoa dinilai besar.
Keadaan yang serba sulit membuat mereka enggan untuk memberikan bantuan lagi
bagi keberlangsungan PAT. Selain itu dari tahun ke tahun keberadaan PAT semakin
bergeser dari tujuan semula. Sepak terjang PAT dirasa sudah melewati ambang
batas kemanusiaan sehingga tak jarang keberadaan mereka dibenci oleh berbagai
pihak. Kebrutalan yang dilakukan personil PAT ditakutkan bagi sebagian orang
Tionghoa akan berubah menjadi balas dendam di kemudian hari kelak (Sulardi,
1994: 91). Mereka mengecam keberadaan PAT karena lebih condong ke pihak Belanda
dan seringkali memusuhi penduduk bumiputra yang tentu saja semakin memperkeruh
hubungan Tionghoa dan Republiken. Dalam
cerpen Pao An Tui karya Dwicipta,
kita akan menemukan korelasi dalam pernyataan Sin Liong tentang sukarnya posisi
Tionghoa setelah adanya Barisan Keamanan Tionghoa:
”Kita memang serba
sulit. Orang-orang di Jakarta dan kota besar lain ramai-ramai membicarakan nasib
babah-babah kaya yang rumahnya terus
dijarah. Dan kita merelakan diri menjadi kacung Pao An Tui. Sementara mereka, babah-babah
kaya itu, yang menyandarkan nasib hartanya pada Pao An Tui tak pernah memikirkan nasib orang- orang miskin seperti
kita, walaupun kita loyal terhadap Republik. Menjengkelkan kalau dipikir-pikir”
(Dwicipta, 2005: 2).
Berbagai dukungan untuk
segera melakukan pembubaran PAT di seluruh Indonesia menjadi agenda serius di
kalangan Tionghoa agar keberadaan badan perlindungan ini tidak terus menerus
digunakan sebagai kepanjangan tangan Belanda. Di mata rakyat dan pemerintah
Indonesia sendiri sudah terpetakan secara jelas bagaimana PAT pada masa
revolusi secara sikap telah memihak “tamu lama”.
Anggota Pao An Tui sedang Latihan Baris-berbaris
(www.budayationghoa.net)
Keberadaan Pao An Tui
akhirnya ditentukan oleh kebijakan politik dimana kesepakatan dibentuknya Uni
Indonesia-Belanda disetujui oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu
wilayah-wilayah yang masuk ke dalam kantong pendudukan Belanda secara otomatis
menjadi negara bagian Republik Indonesia Serikat dan membentuk pemerintahan
sendiri. Perintah pertama yang keluar dari masing-masing pemerintah negara
bagian adalah dibubarkannya milisi-milisi atau badan semi-militer di wilayah
mereka. Tentu saja keberadaan PAT di Indonesia mendapat imbasnya, beberapa
daerah cabang PAT membubarkan diri pada akhir tahun 1949. Angka statistik resmi
mengenai PAT mencatat hingga dibubarkannya badan ini, sekitar 5000 orang
tercatat sebagai anggota – seberapa jauh angka tersebut dapat dipercaya, tidak
diketahui (Somers Heidhues, 1991: 174-175).
Kesimpulan
Keberadaan
Pao An Tui di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sebuah keprihatinan orang
Tionghoa terhadap keberlangsungan hidup mereka di tanah perantauan. Tidak dapat
dipungkiri, orang Tionghoa kerap kali menjadi target sentimen beberapa golongan
yang tidak suka terhadap orang-orang Tionghoa. Alasan masyarakat sipil juga
tidak dapat dipersalahkan karena orang Tionghoa lebih diistimewakan oleh
Belanda pada masa penjajahan. Hal ini ditambah oleh sikap beberapa oknum
Tionghoa yang lebih pro-Belanda pada masa revolusi, meskipun ada juga sebagian
orang Tionghoa yang jelas-jelas mendukung perjuangan Republik. Akan tetapi
tetap saja kekerasan terhadap etnis satu ini berlanjut, hingga akhirnya
dilakukanlah pertemuan di Jakarta dimana salah satu poinnya mendukung
terbentuknya Pao An Tui atau barisan
keamanan Tionghoa.
Tujuan
utama dibentuknya PAT pada awalnya hanya untuk menjaga pemukiman orang Tionghoa
beserta aset-aset ekonominya dari sabotase, akan tetapi ternyata pemerintah
Belanda memiliki rencana lain. Dari awal sengaja pemerintah militer Belanda
ikut campur tangan dalam pembentukannya dan selanjutnya mereka memanfaatkan PAT
untuk berbagai kepentingan militer seperti ikut perang hingga melakukan aksi sweeping di rumah-rumah bumiputra maupun
Tionghoa untuk menghalau mata-mata Republik.
Organisasi
semi-militer ini pada awalnya diakui keberadaannya oleh orang Tionghoa, karena dengan
adanya PAT daerah mereka aman. Akan tetapi karena masalah dana dan sikap PAT
yang semakin hari semakin brutal, pengakuan itu mulai luntur disusul ketakutan
beberapa orang Tionghoa yang tidak ingin ini menjadi ajang balas dendam dan
alat bagi penguasa Belanda. PAT sendiri keberadaannya akhirnya berakhir ketika
diplomasi politik antara dua negara disetujui lewat perjanjian akan dibentuknya
negara Uni Indonesia-Belanda.
Daftar
Pustaka:
Buku:
Abdul
H. Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan
Indonesia. (Bandung: Angkasa, 1977).
Andjarwati
Noordjanah, Komunitas Tionghoa di
Surabaya, 1910-1946. (Yogyakarta: Ombak, 2010).
Benny
G. Setiono, Tionghoa dalam Pusaran
Politik. (Jakarta: ELKASA, 2008).
Cribb,
Robert B. Gejolak Revolusi di Jakarta
1945-1949: Pergolakan antara Otonomi dan Hegemoni. (Jakarta: Grafiti,
1990).
K’tut
Tantri, Revolusi di Nusa Damai.
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).
Nasrul
Hamdani, Komunitas Cina di Medan dalam
Lintasan Tiga Kekuasaan 1930-1960. (Jakarta: LIPI Press, 2013).
Pramoedya
Ananta Toer, Hoakiau di Indonesia.
(Jakarta: Garba Budaya, 1998).
Reid,
Anthony J. S. Perjuangan Rakyat: Revolusi
dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera Timur. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
1987).
__________.
Revolusi Nasional Indonesia.
(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).
Ricklefs,
M. C. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008.
(Jakarta: Serambi, 2008).
Roeslan
Abdulgani, Seratus Hari di Surabaya.
(Jakarta: Yayasan Idayu, 1973).
Tjamboek
Berdoeri, Indonesia dalem Api dan Bara.
(Jakarta: ELKASA, 2004).
Artikel
dalam Buku:
Heidhues,
Mary F. Somers. “Kewarganegaraan dan Identitas Etnis Cina dan Revolusi
Indonesia” dalam Jennifer Cushman dan Wang Gungwu (ed.), Perubahan Identitas Orang Cina di Asia Tenggara. (Jakarta: Grafiti,
1991).
Kahin,
Audrey R. “Pendahuluan”, dalam Audrey R. Kahin (eds), Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan. (Jakarta: Grafiti, 1990).
Van
Langenberg, Michael. “Sumatera Timur: Mewadahi Bangsa Indonesia dalam Sebuah
Keresidenan di Sumatera”, dalam Audrey R. Kahin (eds), Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan. (Jakarta: Grafiti, 1990).
Skripsi:
Sulardi,
“Pao An Tui Jakarta 1947-1949”. Skripsi S-1, Fakultas Sastra, Universitas
Indonesia, 1994.
Internet:
http://cerpenkompas.wordpress.com/2005/11/27/pao-an-tui-1/
Kampung Klebengan, 17 Desember 2013, 12.52 pm.